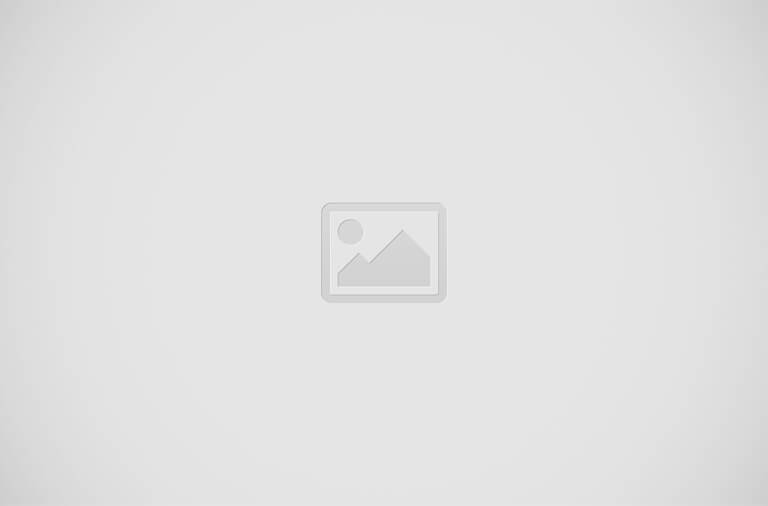Showing posts with label Cerpen. Show all posts
Showing posts with label Cerpen. Show all posts
Thursday, October 20, 2022
TERUNTUK NENEK KAMI TERSAYANG, BAHAGIALAH ENGKAU DI SYURGA-NYA
TERUNTUK NENEK KAMI TERSAYANG, BAHAGIALAH ENGKAU DI SYURGA-NYA
Oleh : @diiana.rembulan_11
Telah lama kita tidak bersua, sudah tujuh tahun lamanya setelah engkau meninggalkan dunia. Kepergianmu menyisakan kesedihan nan teramat dalam bagi kami keluarga tercintamu yang ditinggalkan. Saat ini bagaimana kabar nenek di sana? Apakah nenek baik-baik saja di sana? Aku harap, saat aku menuliskan tulisan ini, nenek sedang tersenyum sembari ditemani oleh malaikat syurga.
Nek, masih ingatkah dahulu di kala nenek gemar menjahitkan bajuku? Yah, baju yang nenek jahit sendiri. Hingga nenek rela terjaga dan tertidur pulas demi menjahitkan baju untukku. Bahkan nenek juga selalu mengajarkanku untuk menjahit. Masih ingatkah dahulu, ketika aku pulang sekolah engkau selalu menyiapkan makan siang untukku sebagai bentuk kasih sayangmu. Aku rindu dengan usapan tangan nenek yang selalu membelai lembut kepalaku. Rindu dengan candaan ringan yang selalu nenek lontarkan di momen-momen bahagiaku. Bahkan, aku rindu saat nenek memberiku nasihat yang begitu menyentuh. Pun, aku rindu dengan dongeng singkat nenek sebelum aku tertidur pulas perihal 'Zaman Indonesia Di Masa Penjajahan Belanda dan Jepang'. Ahhh ... andai nenek masih ada di sini, kita pasti masih saling bertukar cerita.
Tahukah engkau, wahai wahai nenek kami tercinta? Semenjak kepergianmu ada banyak hal yang terjadi di dunia ini dalam kehidupan kami dan kehidupanku yang kini sudah mulai beranjak dewasa. Lihatlah, cucu kecilmu nan lugu kini sudah menjadi wanita dewasa. Aku kini sedang menjalani studiku dan aku berharap bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu agar dapat mewujudkan cita-citamu nenek. Dan kini, sungguh, aku ingin nenek masih ada di sini menjadi saksi dan melihat langsung wisudaku nanti, serta menjadi saksi pertumbuhan dan perjalanan hidupku hingga aku tumbuh menjadi sosok wanita yang tangguh dan dewasa.
***
Hari itu akhirnya tiba. Hari di mana kesehatan nenek mulai menurun dan hanya bisa berbaring lemas di atas pembaringan. Aku selalu mengutuki diri dan hari itu. Aku tidak pernah berharap hari itu benar-benar terjadi di hidupku. Yah, hari di mana kesehatan nenek mulai menurun. Aku semakin jelas melihat adanya jejak guratan tua di wajahnya. Engkau yang tak lagi nampak muda dan tak lagi bisa menyiapkan hidangan spesial untukku. Nenek lebih banyak terbaring lemah di atas pembaringan.
Maafkan aku, Nenek. Ketika dulu engkau menyuruhku, terkadang masih sering kuabaikan. Bahkan pada saat-saat terakhirmu pun aku dan keluargamu yang lain tidak mengetahui engkau telah pergi.
"Maafkan kami, Nenek! Pada saat terakhirmu kami belum bisa berada di sampingmu.", gumamku ketika aku selalu diingatkan kenangan tentang nenek
Sungguh, waktu itu kami benar-benar sedang tertidur pulas hingga keesokan harinya kami baru mengetahui bahwa engkau telah tiada. Maafkan cucumu yang terkadang masih sering mengabaikanmu. Sebab, dahulu ketika aku remaja, aku masih belum mengerti betapa sakitnya diabaikan. Kini kami mulai menyadari bahwa kami tidak benar-benar memanfaatkan waktu pertemuan kita di dunia dengan sebaik-baiknya. Kami membuang waktu yang begitu sangat berhargademi dunia kami sendiri. "Maafkan kami, Nenek."
Sekarang hanya tinggal rasa sedih dan penyesalan yang masih tersisa. Sampai detik ini pun, aku terkadang masih menyesali diri sendiri. Mengapa dahulu aku tidak selalu berada di sampingmu? Mengapa aku lebih memilih mengabaikan daripada menemani? Yah, mungkin rasa sesallah yang kini selalu menjadi alarm penanda bahwa aku tidak boleh lagi mengabaikan orang-orang yang selalu menyayangiku di dalam hidupku.
Nenek, tahukah engkau bahwa sekarang aku selalu merasa cemburu ketika ada kawanku yang masih memiliki sosok seorang nenek. Yah, aku cemburu pada mereka yang masih dekat dan bisa merawat neneknya. Sedangkan mengapa nenekku dipanggil lebih dahulu? Melihat kedekatan mereka dengan neneknya membuatku rindu dengan kenangan yang kita lalui bersama. Kenangan saat kita saling bertukar cerita atau saat nenek selalu menuruti segala keinginanku dengan selalu menyiapkan menu spesial untukku. Kenangan ketika nenek bercerita perihal kehidupan kepada kami, daaaan ... aaahh ... kenangan bersama nenek tidak akan pernah ada habisnya jika kutuliskan semua di sini.
***
Namun, asal nenek tahu kenangan manis bersama nenek akan selalu tersimpan rapi di benakku. Di dalam hati kami, juga dalam catatan kecil yang selalu kusebut sebagai 'diary'. Dan bila suatu esok nanti waktuku telah tiba untuk benar-benar berperan sebagai seorang nenek, aku akan mencontoh sifatmu persis seperti yang pernah engkau ajarkan padaku. Yah, aku banyak belajar dari nenek. Belajar betapa berartinya dalam menghargai, menerima dan mencintai dengan tulus.
Nenek, maafkan aku. Aku belum sempat mengatakan perasaanku padamu bahwa, "Aku mengagumi dan sangat menyayangi sosokmu."
Yah, rasa ini belum terlalu jelas kurasakan saat usiaku masih remaja. Namun, kini aku tahu benar bahwa nenek sudah berjasa memberikan masa remaja nan membahagiakan serta kehidupan yang sangat berarti untuk kami anak-anakmu, cucu-cucumu yang lain, jua kerabat terdekatmu. Kami sungguh sayang nenek. Kami berharap semoga kami bisa dipertemukan kembali kelak di syurga-Nya.
*** selesai ***
Cirebon, 10 Oktober 2022
Dari kami,
Anak, menantu, cucu, uyut, dan kerabat terdekatmu yang sudah sangat merindukanmu.
✍🏻: cucumu, Diana Pita
MENGENANG 7 TAHUN WAFATNYA ALMARHUMAH IBU KURNIAH BINTI BAPAK ABDULLAH
10 Oktober 2015 - 10 Oktober 2022
Lahumul Fatihah ...
0
comments
Sunday, May 31, 2020
Cerpen | Ulah Lanang Segede Sepur (Ular Jantan Sebesar Kereta) part 3
Oleh: Lukman
Hari demi hari suasana desa nampak begitu berbeda. Angin yang biasa datang untuk menyejukan tubuh, kini berganti membawa wabah aneh. Kebanyakan korbannya adalah anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun. Tubuhnya panas dan kulit mereka menjadi kasar bak sisik ular. Entah siapa yang mengirimkan wabah ini. Namun yang pasti, ini merupakan sebuah tanda besar.
Namun, tak semua orang lantas mempercayai hal-hal yang dianggap sebuah mitos dan tahayul. Bahkan, Pak Dharmo justru menganggapnya sebagai wabah biasa di musim panceklik. Sebenarnya tabib dan dukun di desa sudah tak sanggup untuk mengobati anak-anak itu. Hingga daun-daun muda itu harus berguguran sebelum waktunya tiba. Jeritan tangis memecah dinding langit yang kokoh. Tetap saja, walau pun demikian Pak Dharmo tak mempercayainya sebagai kenyataan dan tanda besar. Padahal dukun dan tabib itu berkata bahwa mereka didatangi sesosok makhluk besar dan panjang, setiap kali setelah mengobati anak tersebut.
“Pak, aku beberapa kali didatangi makhluk itu. Dia selalu meneriakan namamu dan beberapa warga desa yang lain.” Ucap dukun yang berdiri tegap di ruang aula rumah Pak Dharmo.
“Halah, mimpi itu ‘kan cuma bunga tidur. Itu cuma mimpi Mbah! Udahlah ga usah kamu pikirin lagi!” ketus Pak Dharmo.
“Tapi –” suara dukun itu mendadak terhenti dan berubah menjadi lebih besar
“Dharmo! Waktumu hanya tujuh hari lagi! Ke mana pun kamu lari, takdir tak akan pernah salah alamat. Ingat itu baik-baik!” Mata dukun itu merah nanar dan sambil terus meneriaki Pak Dharmo,
Mendadak ruangan itu menjadi lebih mencekam, jendela-jendela kayu bak sayap burung yang hendak terbang. Terus mengepak dihembus angin yang entah dari mana datangnya. Aroma bunga kantil pun serasa sengaja ditaburkan ke semua hidung orang yang ada di ruangan itu. Namun, Pak Dharmo menyikapinya benar-benar dingin dan acuh tak acuh.
Beberapa menit kemudian, dukun itu lekas sadarkan diri. Wajahnya mulai bercampur aduk, tanpa spasi dan koma dia langsung meninggalkan rumah Pak Dharmo. Aneh, Pak Dharmo tak sedikit pun merasa bersalah dan ketakutan. Ia justru menertawakan makhluk yang merasuki dukun tadi bersama teman-temannya.
“Setan gebleg! Lah, aku diwedini kaya ngono ya ra bakal wedi. Hahaha (Lah, saya ditakuti kaya begitu ya ga bakal takut).” Tawanya dengan segala kejumawahannya.
Semua orang di rumah itu tertawa terbahak-bahak. Mereka bahkan tak menggubris omongan warga lain. Malah, asyik berpesta ria dengan beberapa minuman keras yang sedari tadi bertengger di meja kaya. Orang gelamor seperti Pak Dharmo memang tidak akan mudah mempercayai tahayul seperti itu walau pun ia melihat dengan mata kakinya.
***
Dua hari setelah kejadian itu, dua puluh persen dari jumlah anak-anak di desa sudah pergi dan tinggal di pelukan bumi. Para warga semakin cemas dan takut. Bahkan sampai ada yang pergi meninggalkan desa. Pak Dharmo? Seperti biasa, dia acuh tak acuh terhadap warganya.
Hingga malam itu telah tiba. Pak Dharmo lari kocar-kacir dengan putus asa. Berteriak meminta pertolongan tetapi tak ada satu pun yang mampu mendengarnya. Suara makhluk itu terus menggema di antara pohon-pohon besar. Burung-burung berterbangan hendak menjauh. Langkah Pak Dharmo terhenti kala melihat sebuah gua besar yang menurutnya tempat teraman untuk bersembunyi. Namun sayang disayang, ia terperangah kala melihat teman sejawatnya dililit dan hendak dilahap oleh seekor ular raksasa.
“Mu ... Muklis!” ucapnya terkaku dengan tubuhnya yang tak berhenti gemetaran.
“Tolong aku, Dharmo!” teriak Jono
“Ah? Ka–kamu juga Jon!”
Pak Dharmo hanya terdiam kaku, tanpa pikir panjang ia justru berlari meninggalkan teman sejawatnya itu. Tega betul, teman pestanya ia tinggalkan dan dibiarkan mati dilahap oleh ular itu. Ia terus berlari mencari tempat berlindung. Wajahnya pucat pasih, guyuran keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya.
Istrinya mencoba untuk membangunkannya, tetapi hal itu sia-sia. Namun, matanya masih menutup dan sesekali mengigau tak karuan. Rupanya dia sedang bermimpi didatangi oleh makhluk buas itu. Dengan sekujur tubuhnya yang dipenuhi oleh keringat dingin, dia masih tak kunjung sadarkan diri juga.
“Tolong! Tolong! Tolong!” Pak Dharmo terus merancau tak karuan.
Dia hanya terus mengucapkan itu dalam tidurnya. Hingga beberapa tokoh adat didatangkan termasuk Ki Agung. Namun, hanya Ki Agung yang menyadarkannya. Dengan segenap ilmu yang ia punya, sebuah daun kelor diletakan di dahi Pak Dharmo. Dia tahu dengan daun itu, dapat menetralisir gangguan gaib apa pun.
“Dharmo, bangun Mo!” bisik Ki Agung di telinga kiri Pak Dharmo.
“Tidaaak ... hah!” Dengan napas yang terengah-engah Pak Dharmo bangun dari mimpi buruknya.
“Sekarang kamu ceritakan apa yang telah terjadi, Mo!” ucap Ki Agung, “Ratmi tolong kamu ambilkan air putih dulu untuk suamimu.”
“Ini Mas. Silakan diminum dulu.” Ucap Ratmi sambil menyodorkan air putih ke mulut Pak Dharmo.
Namun. Pak Dharmo tak mengatakan apa pun kepada semua orang. Walau dipaksa sedemikian rupa, dia enggan mengatakannya dan lebih memilih untuk berbaring di ranjangnya kembali. Orang-orang pun merasa kesal dan beranjak pergi dari rumah Pak Dharmo.
Setelah dua hari dari kejadian itu Muklis dan Jono tewas secara mengenaskan. Jasad kedua ditemukan di ladang milik warga dengan wajah yang membiru dan seperti bekas lilitan. Tak ada satu orang pun yang tahu penyebab kematian mereka berdua. Pak Dharmo yang mengetahui teman sejawatnya tewas mengenaskan itu, badannya menggigil lagi.
“Tinggal tiga hari lagi masamu Dharmo.” Seseorang membisiki Pak Dharmo yang entah dari mana datangnya. Wujudnya pun tak nampak mata. Pak Dharmo terus menengok dan mencarinya ke sana ke mari. Namun, wujud orang yang membisikinya tadi benar-benar tak ada. Dia hanya seorang diri di kamarnya, istrinya pun sedang keluar.
***
“Aduh Gusti, sebentar lagi dia akan datang.” Resah Ki Agung Kusumo, “Ndok, cepet bereskan pakaianmu dan bawa prabotan yang bisa dibawa!”
“Iya Pak.” Ucap Leli dan bergegas menuruti perintah Ki Agung Kusumo.
Suara erangan terdengar keras memenuhi sudut-sudut desa. Semua orang keheranan mendengarnya. Ada juga yang merapihkan pakaian dan beberapa prabotan rumah seadanya. Syamsul lari tungang langgang dari arah pemakaman.
“Dia ... benar-benar datang!” Wajah Syamsul pucat pasih dan dipenuhi oleh keringat dingin.
“Siapa Syul?” tanya seorang warga.
“Bereskan pakaian kalian, lalu cepet lari!” teriak Syamsul sambil meneruskan larinya.
“Hah?! A .. apa itu? Lari!” teriak seorang warga
“Ulah Lanang Segede Sepur!” Semua warga meneriakan makhluk itu.
Sesosok ular besar itu melata dengan cepet dari arah datangnya Syamsul. Benda apa pun setiap dia melewatinya akan dihancurkan tanpa tersisa. Dengan tubuhnya yang sebesar kereta api itu, tentu membuatnya sangat mudah menghancurkan apa pun. Berbondong-bondong warga berlarian menghindari dan menyelamatkan diri dari makhluk itu.
Rumah warga banyak yang hancur tak bersisa. Mayat-mayat warga pun banyak yang bergeletakan di jalan. Rumah segagah apa pun tak akan bisa melindungi mereka dari amukan makhluk ini. Tempat perjudian, pelacuran, dan warung remang-remang hancur berkeping-keping. Semua warga panik dan putus asa. Nyawa mereka sudah berada di ujung tanduk.
Hanya satu tempat yang tidak terjamah oleh ular itu. Tempat itu adalah mushola yang beberapa bulan lalu tak terjamah oleh siapa pun. Ternyata ular itu enggan untuk menghancurkan bangunan ini. Dia pun secepat kilat mengejar lelaki paruh baya yang tak lain adalah Pak Dharmo.
“Tidak, tolong maafkan aku!” rintihnya memelas
“Sstttzt.” Ular itu hanya terus berdesis tak menghiraukan Pak Dharmo yang terus lari ketakutan.
“Dharmo! Cepat sembunyi di sini!” teriak Ki Agung dari dalam mushola
Namun, dia tak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Ki Agung Kusumo. Dia terus berlari mencari pertolongan. Di bawah pohon besar dekat pemakam, dia terjebak dan tak bisa lagi berlari. Kakinya tersandung batu dan tak bisa digerakan lagi. Tubuhnya dililit sampai tak lagi bernapas, lalu ular itu melahapnya dengan cepat. Sayang, semua kekuasan, kedudukan, kekerabatan, dan hartanya tak dapat menyelamatkannya dari ganasnya sang Ular.
Setelah itu, bumi diguyur hujan deras selama tiga hari. Penguasa langit ingin membersihkan sisa-sisa kehancuran di desa tersebut. Warga yang masih selamat, keluar dari mushola untuk memastikan ular itu sudah tak ada lagi. Udara segar datang dari arah barat, menandakan musibah itu telah berlalu. Sejak hari itu, warga tak lagi mendengar dan melihat Pak Dharmo. Istri dan anaknya pun entah ke mana bak ditelan bumi.
Warga kembali membangun desanya. Cerita ini akan terus menjadi sebuah nasihat besar untuk generasinya mendatang. Mereka akhirnya pun sadar bahwa tak ada kekuasaan yang dapat menandingi kehendak-Nya. Keangkuhan dan keserakahan akan membawakan alat penghancur massal yang tak terelakan. Semenjak hari itu juga rumah peribadatan tak pernah sepi.
Friday, April 24, 2020
Cerpen | Ulah Lanang Segede Sepur (Ular Jantan Sebesar Kereta) part 2
Oleh : Wawat Qomariyah
Setelah mendengar segala cerita si Kakek semalam, Parman dan Komar gelisah bukan main. Suasana ronda
mendadak menjadi mencekam luar biasa, bukan lagi ketakutan pada harta benda
warga yang mungkin saja hilang. Takutnya melebihi semua itu. Apalagi saat si
Kakek pulang meninggalkan mereka berdua di pos ronda, atmosfer ketakutan
bertambah berlipat-lipat. Jangankan untuk tertidur seperti ronda-ronda sebelumnya,
untuk sekadar mengantuk pun mereka tak bisa. Mata mereka masih terjaga sempurna
hingga fajar menyingsing dengan segala pergumulan hebat dalam masing-masing
benak.
“Man, menurut sampeyan apa yang dikatakan Ki Agung
Kusumo itu bener apa ngga, ya?” Komar bertanya pada Parman saat perjalanan pulang. Ini percakapan
pertama mereka lagi setelah semalan terdiam dengan pikiran masing-masing.
“Ora ngerti aku, Mar. Semaleman aku juga mikirin
terus itu. Mau percaya sama begituan udah gak zaman, kalo gak percaya tapi yang
ngomong Ki Agung. Mana mungkin Ki Agung bohong? Apalagi Ki Agung sudah lama
hidup, pasti banyak yang dia ketahui ketimbang kita.” Jawab parman.
“Tapi ya kalo sampe bener aku takut banget, Man.” Ujar
Komar dengan raut muka panik. Parman hanya menjawab dengan desahan berat, dia
juga sama panik.
Mereka tetap saling diam hingga berpisah di persimpangan
karena arah rumah mereka berbeda.
Pagi dimulai seperti biasa, seperti tak ada cerita apapun
tadi malam karena memang hanya Komar dan Parman yang tahu. Setiba di rumah
masing-masing mereka langsung tertidur tanpa memedulikan seeruan Tuhan yang
mereka dengar dalam perjalanan pulang. Aktifitas warga berjalan tanpa
terpengaruh apapun, tidak terkecuali dengan warung remang-remang yang sudah ada
hampir di setiap sudut desa.
Ki Agung Kusumo pagi ini terduduk dengan pandagan mata
kosong ditemani teh hangat buatan putrinya, Laeli.
"Kenapa toh, Pak? Tehnya diminum nanti
dingin." Tegur Laeli yang melihat Ki Agung bergeming, melamun menatap
langit.
"Dulu Bapak ndak percaya, Nduk. Dulu
kakek buyut Bapak cerita ini dan Bapakmu ini ndak percaya." Gumam
Ki Agung membuat Laeli mengernyitkan dahi.
"Maksudnya apa toh, Pak?" tanya Laeli,
tapi tak ada jawaban dari bibir keriput Ki Agung.
Laeli memutuskan untuk masuk ke dalam rumah,
menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas. Baru saja ia mau melangkahkan
kakinya, tiba-tiba langit di sebelah timur mendadak menghitam. Terlalu cepat
jika itu dikatakan mendung, karena beberapa detik yang lalu matahari masih
bersinar dengan sangat gagah. Dari kejauhan terlihat seperti gumpalan awan
memanjang, melintang menghalangi cahaya bagaskara.
Laeli menghentikan langkahnya, Ki Agung bangkit dari
duduknya. Mata tuanya mengkilap beringas, dahinya mengkerut, tangannya
mengepal, hatinya benar-benar cemas. Kesiur angin kencang berhembus dari arah
timur yang berarti dari arah pemakaman. Suara gemuruh bersahutan seperti akan
turun hujan lebat.
"Ono opo toh, Pak?" Tanya Laeli gemetar,
Ki Agung tak menjawab. Laeli tahu dari gelagat Ki Agung bahwa ini bukan
pertanda baik.
Suasana mencekam itu hanya beberapa menit saja, setelah
itu suasana kembali normal. Langit kembali cerah, tak ada lagi gumpalan awan
hitam memanjang yang menutupi sinar bagaskara. Namun tak berapa lama kemudian,
seseorang dari arah pemakaman lari tunggang langgan tanpa alas kaki. Wajahnya
pucat pasi bak tak ada darah yang mengaliri. Beberapa kali ia terjatuh, akn
tetapi segera bangkit lagi dan kembali berusaha lari. Dia Syamsul, tukang gali
kubur di Desa Sukojiwo. Ki Agung berlari
menghampiri, Laeli menyusul.
"Ono opo toh, Lek? (Ada apa, Nak?)" tanya Ki Agung khawatir. Syamsul tak cepat menjawab,
beberapa kali ia menoleh cemas ke belakang seolah sesuatu yang menakutkan
tengah mengejarnya.
"Kamu yang tenang dulu, tarik nafas!" Perintah
Ki Agung, Syamsul menurut.
"Iku ono iku loh Ki ...," nafas Syamsul terengah-engah tak bisa
melanjutkan kata-katanya.
"Ono opo?"
"Ono ... ono ... ono ... ulah, Ki. Ono ulah segede sepur, Ki.(Ada ... ada ... ada ... ular, Ki. Ada ular segede kereta, Ki.)” Jawab Syamsul gemetar. Wajahnya makin pucat. Wajah Ki Agung
dan Laeli pun memucat.
"Sekarang, cepat kamu pulang! Kasih tau kepada warga
yang lain untuk masuk ke rumah, tinggalkan maksiat, dan banyak eling
(ingat) sama Gusti Yang
Agung!" perintah Ki Agung, Syamsul mengangguk paham. Setelah berpamitan
dia langsung berlari pulang.
"Nduk, mlebu ning umah. Elinga maring Gusti sing akeh (Nak, masuk ke rumah. Banyaklah ingat
sama Tuhan)!" perintah Ki Agung pada Laeli, Laeli
mengangguk ta'dzim lalu segera masuk ke dalam rumah.
Ki Agung Kusumo bergegas, langkahnya masih terlihat kokoh
untuk seusianya. Matanya mendelik tajam, tak ada lagi tampang ramah yang
disukai warganya. Beberapa kali Ki Agung bertemu dengan warga, tapi tak ada
satupun dari mereka yang menyapa seperti biasa. Raut wajah Ki Agung yang
berbeda, membuat tanda tanya besar di benak warga desa. Belum lagi kejadian
yang baru saja terjadi. Beberapa warga yang berpapasan hendak bertanya perihal
langit yang tiba-tiba menghitam namun tak lama kemudian kembali cerah, tapi tak
ada satu pun kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya bisa menerka, mungkin
sesuatu yang buruk sedang atau akan segera terjadi. Sepasang mata mereka hanya
mampu menatap punggung renta Ki Agung yang semakin menjauh.
Langkah Ki Agung berhenti di sebuah rumah dengan
pekarangan luas. Suara riuh terdengar tanpa rasa cemas. Barangkali mereka
terlalu sibuk menikmati musik gamelan diiringi tarian tradisional dari
gadis-gadis berparas ayu, hingga tak sadar apa yang baru saja terjadi. Ki Agung
mengelus dada, menghela napas berat. Musik dan tarian itu memang tradisional
bernuansa budaya bangsa, tapi entah ditambahi apa sehingga rasanya malah tak
patut dipertontonkan. Entah dari pakaian sang penari, tariannya yang
dilebih-lebihkan, atau dari penonton yang bersorak-sorai sambil menggoda
gadis-gadis itu.
Musik mendadak terhenti ketika salah satu dari mereka
melihat kehadiran Ki Agung setelah itu semua mata hampir tertuju kepada sosok
tua yang penuh karisma itu. Pak Dharmo pemilik rumah sekaligus Kepala Desa Sukojiwo
juga ikut menoleh, dia tersenyum licik saat melihat siapa yang datang.
"Oh Ki Agung Kusumo, selamat datang, Ki!" sambut Pak Dharmo dengan nada semi mengejek sambil
menghampiri.
"Ada apa gerangan seorang Ki Agung Kusumo datang ke
rumah saya? Jika dipikir-pikir ini kali pertama Ki Agung mengunjungi rumah saya, setelah saya terpilih menjadi Kepala Desa." Ucap
Pak Dharmo sambil tertawa dibuat-buat.
"Hentikan semua ini, Dharmo!" Ki Agung berkata
tegas. Suasana hening sejenak tercipta, lalu buyar ketika Pak Dharmo tiba-tiba
tertawa.
"Waaah, apa maksud Ki Agung itu? Mbok ya
kalau bertamu itu masuk loh, Ki. Sini kita obrolkan di sini!" Ucap Pak
Dharmo tanpa tasa hormat.
"Dharmo, yang kamu lakukan sudah diluar batas.
Sebaiknya kamu berhenti, hanya soal waktu dia akan muncul." Ancam Ki
Agung. Semua orang yang ada di sana saling melempar pandangan, mencoba mencerna
apa yang tengah terjadi.
"Maksud Ki Agung, Ular penunggu pemakaman itu?
Hahaha." Pak Dharmo tertawa menjijikkan. Ki Agung mulai naik pitam.
"Itu cuman mitos, Ki. Mitos. Hahaha." Pak
Dharmo kembali tertawa, menganggap semua yang diceritakan hanya sebagai
lelucon.
"Terserah kamu, Dharmo. Tapi, Syamsul penggali kubur
dia melihat secara langsung. Aku hanya memperingatkan. Ingat ketika waktu itu
tiba bukan hanya kamu yang celaka, tapi seluruh warga ikut dalam bahaya. Satu
lagi, aku peringatkan kauorang pertama yang mungkin dalam bahaya." Ucap
Ki Agung sungguh-sungguh. Raut wajah Pak Dharmo berubah bengis, menatap tak
suka pada Ki Agung.
“Maaf, Ki. Saya tidak akan percaya hal bodoh seperti itu.
Saya tidak suka jika ada yang menghalangi jalanku apalagi hanya dengan dongeng
murahan seperti itu. Saya masih menghormati Ki Agung sebagai tetua Desa, tapi
jika terus seperti ini tidak ada pengecualian sekali pun untuk seorang Ki Agung Kusumo.” Bisik Pak Dharmo
bengis tepat di sisi telinga Ki Agung. Raut wajah Ki Agung Kusumo masih sama,
tak bersahabat sama sekali.
“Kalian semua, lebih baik kalian hati-hati!” Ki Agung
berkata tegas dengan nada suara meninggi sambil melempar pandangan pada
orang-orang yang berada di pekarangan rumah Pak Dharmo. Setelah itu Ki Agung
pergi.
Langkah Ki Agung terhenti.
Wednesday, April 15, 2020
Cerpen | Ulah Lanang Segede Sepur (Ular Jantan Sebesar Kereta) part 1
Seorang
kakek berdiri di teras rumahnya yang keriput dimakan oleh zaman. Tatapnya amat
kosong, ia terus menatap langit dengan penuh kegundahan. Pohon-pohon melambai
diterpa hembusan angin pagi. Tak ada yang tahu apa maksud dirinya menatap
dengan penuh keluh itu. Tiba-tiba lamunannya terhenti oleh derap langkah kaki
yang ia kenali dari jauh. Seorang perumpuan paruh baya keluar dari dalam rumah
dan menyapanya dengan lembut.
“Pak?
Ini teh hangatnya.” Ucap perempuan itu.
“Iya
terima kasih. Nak, dunia ini sudah menua. Jagaen
awak lan batin piyambek (jagalah badan dan batinmu).” Pinta kakek itu.
“Iya
Pak, insyaallah Laeli akan menjaga diri selalu.” Kata perempuan itu sembari
menuangkan teh ke gelas.
Hari
itu memang amat cerah tetapi sedikit berawan. Kambing-kambing sedari tadi
digiring pergi ke ladang untuk mencari makan oleh tuannya. Awan bergerak
mengikuti seorang kakek yang tadi baru saja meneguk teh hangatnya. Kakek itu
bukanlah orang biasa, ia amat disegani oleh seluruh penduduk desa. Maklum, dia
adalah orang yang paling dituakan di desa itu, bahkan usianya kini sudah hampir
seratus tahun atau lebih tepatnya sembilan puluh delapan. Dengan berbekal
tongkat kayu di tangan kanannya, dia pun terus melangkah menuju balai desa.
Sudah
enam tahun berlalu semenjak pergantian Kepala Desa Sukojiwa, desa itu banyak
mengalami penderitaan dan kerugian bagi para penduduknya. Kebun dan pertanian
mengalami banyak sekali kegagalan. Hama dan cuaca yang tak menentu membuat
tanaman padi tak bisa dipanen dengan maksimal. Akibatnya, warga pun mulai
berpikir tak lazim untuk mendapatkan sesuap nasi. Banyak cara kotor yang mereka
lakukan, salah satunya adalah pesugihan dan perampokan atau pembegalan.
Mereka hanya ingin terus hidup walau pun
dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Dulunya memang banyak orang yang
mengecam akan hal tersebut, dan tak sedikit dari mereka dikucilkan karena melakukannya.
Namun, nafsu sudah membunuh setiap sendi kemanusiaan mereka. Seiring
berjalannya waktu, mereka pun akhirnya memaklumi hal tersebut dan
berbondong-bondong ikut melakukan kejahatan.
Ayat-ayat
Tuhan telah tertutup oleh nafsu yang terus membuncah tanpa batas. Rumah-rumah
ibadah sudah jarang ditempati oleh mereka. Bahkan, tak sedikit tempat ibadah
yang kotor dan dipenuhi oleh sarang laba-laba. Semua orang beranjak
meninggalkan ayat-ayat Tuhan. Takut? Rasanya, takut kepada-Nya sudah tak ampuh
untuk mengobati perut yang lapar.
Hari
ini adalah hari pemilihan Kepala Desa yang baru. Ada dua orang yang mencalonkan
diri sebagai Kepala Desa yang baru, yaitu Pak Setyo dan Pak Dharmo. Keduanya
merupakan orang yang disegani pula oleh para warga. Pak Setyo yang kini berusia
lima puluh tahun adalah seorang petani dengan luas sawahnya yang
berhektar-hektar. Sedangkan, Pak Dharmo berusia lima puluh lima tahun adalah
seorang pengebul minyak kepala yang amat kaya.
***
Enam
bulan berlalu semenjak terpilihnya Pak Dharmo sebagai Kepala Desa yang baru.
Namun, desa itu tetap saja belum bisa meninggalkan kebiasaan buruknya. Perampok
terus menjarah setiap pintu-pintu rumah warga. Warung remang-remang justru
malah semakin banyak disinggahi pengunjung. Rumornya, Kepala Desa yang baru
justru mendukung adanya warung tersebut dengan dalih untuk pemasukan dana desa
yang amat lumayan banyak.
Warga
yang masih sadar akan pentingnya seorang pemimpin bagi masyaratnya sebagai
teladan, berusaha mengingatkan. Mereka berbaris di depan kantor desa dengan
berpakaian khas masyarakat Jawa pada umumnya.
“Pak
Kades, kami di sini untuk berunjuk rasa dan menolak adanya warung remang-remang
yang Bapak dukung itu. Bapak harus segera menutupnya, betul?” teriak seorang
warga
“Betul!”
seru warga lain.
“Hahaha
… siapa namamu? Emangnya kamu siapa?” tanya Pak Dharmo sembari menunjuk warga
yang berorasi tadi.
“Saya
Sukarya, warga dusun dua Pak.” Tegas Sukarya
“Baiklah,
saya tidak mau ada yang terluka di sini. Saya tegaskan lagi, semua ini demi
kalian warga-warga yang miskin. Yang ga punya duit dan sengsara. Sudah, kalian
cepet bubar dari sini atau mau aku paksa bubarkan dengan anak buahku!” perintah
Pak Dharmo.
Seperti
itulah perangainya yang kasar dan tak pernah takut akan balasan dari Tuhan
beserta bala tentara-Nya. Namun sayangnya, setelah kejadian itu Sukarya tak
pernah terlihat lagi oleh para warga. Menurut istrinya, malam setelah unjuk
rasa di balai desa tadi, lalu tiba-tiba suaminya dibawa oleh segerombolan orang
bercadar hitam. Banyak warga yang mencoba mencarinya tetapi tak kunjung ada
kabarnya kembali ke rumah.
Pada
malam berikutnya, warga yang piket meronda sedang asik duduk di posnya.
Secangkir kopi dan serdadu catur menemani dinginnya malam di pos ronda. Mereka
berdua pun membicarakan kejanggalan yang terjadi atas hilangnya Sukarya.
“Eh,
semenjak demo waktu tadi pagi. Mas Sukarya tak pernah ada kabarnya lagi loh dan
istrinya pun mencarinya tapi ya, ga ketemu juga.” Ujar Parman
“Jangan-jangan,
dia diculik sama Pak Kades?! Soalnya kata orang-orang, Pak Kades tuh orangnya
gak suka kalo ada yang ngebantah omongannya apalagi sampai ngelawan kayak gitu.
Terlebih lagi, katanya dia itu ikut pesugihan juga loh! Jangan-jangan Sukarya
dijadiin tumbal dia lagi, ih!” kata Komar
“Ah,
yang bener? Kamu jangan asal ngomong entar kalo ga bener bisa-bisa jadi fitnah
loh!” tegas Parman
“Oalah,
orang-orang juga udah pada tahu, kok! Udah banyak orang juga yang pernah liat
Pak Kades sering keluyuran di malam Jum’at Kliwon, terus besok paginya ada aja
rumah warga yang kehilangan duitnya. Aku ga pernah bilang yang enggak-enggak,
tapi faktanya emang kayak gitu.” Ujar Komar.
Di
tengah pembicaraannya, sesosok hitam mendekati mereka. Ah, ternyata itu kakek
yang paling disegani di desa itu. Sembari melemparkan senyuman ke mereka, kakek
itu meminta keduanya untuk memberikan tempat duduk. Namun setelah duduk, raut
wajahnya berubah menjadi merah nanar. Intonasinya pun ikut berubah aneh dan tak
seperti biasanya, setelah mendengar cerita kejanggalan yang terjadi di desanya.
“Dia
akan datang!” ucapnya
“Dia
siapa, Kek?” tanya Parman
“Aduh
Gusti, ampuni dosa-dosa kami.” Ucapnya lagi walau sedikit samar
“Sebenarnya
dia siapa, Kek?” tanya Parman lagi.
“Dia
adalah makhluk penjaga desa ini dari jaman keraton dulu. Dia adalah jelmaan
penguasa alam ghaib. Tubuhnya amat besar dan panjangnya koyo sepur (seperti kereta).” Ujarnya dengan mata merah nanar.
Malam
itu semakin mencekam, udara mendadak pengap dan membuat sesak bernafas. Awan
gelap digiring menutupi setiap wajah langit dan bulan. Gemuruh dan kilat silih
berganti memecah keheningan malam. Mereka terus mendengarkan dengan khusu
cerita kakek tadi. Bagaimana mungkin, makhluk itu masih ada di jaman yang sudah
modern ini. Begitulah yang ada di pikiran mereka berdua. Rasanya amat sulit
mempercayai ucapan sang kakek tadi.
Menurut
sang kakek, makhluk ini tinggal di tempat pemakaman warga. Dia sedang tertidur
panjang di sana. Hanya orang tertentu yang dapat melihatnya secara langsung. Sepanjang
usia bumi, dia baru dua kali muncul ke permukaan. Bukan tanpa sebab ia muncul
ke permukaan dan menampakan diri kepada semua orang. Hanya ada satu alasan atas
kehadirannya, yaitu: untuk menghancurkan peradaban manusia dengan pemimpinnya
yang lalim dan tak bermoral.
Bersambung ….Tuesday, January 29, 2019
Cerpen | Gugur
Oleh: Dwi Zayanti
***********
California, 15 Oktober 2002
Musim gugur telah tiba. Daun-daun mulai berjatuhan di tanah, memisahkan diri dari batang dan ranting tempatnya tinggal. Entah karena memang telah layu ataupun terkena hembusan angin.
"Kau tahu kenapa di setiap musim gugur daun-daun selalu berjatuhan, George?" tanya ibu suatu hari ketika kami sedang menikmati coklat panas di halaman belakang rumah sambil mengamati sebuah daun maple yang melayang di udara.
"Tidak, Bu. Bisakah Ibu memberi tahuku?" aku bertanya tepat sesaat setelah daun itu menyentuh tanah. Warna mereka sama; merah bata.
"Karena ketika musim gugur, sinar matahari sangat sedikit menjamah bumi. Pohon tidak memiliki cukup waktu untuk membuat cadangan makanan. Sehingga ia harus merelakan daun-daun itu jatuh, meninggalkannya sendirian." Angin lembut menerpa wajah kami saat ibu mengatakannya.
"Kadang-kadang, kita harus menjadi seperti pohon di musim gugur, George. Merelakan sesuatu yang berharga pergi. Tapi jangan khawatir, setelah musim dingin berakhir, Tuhan akan mengganti daun-daun itu dengan dedaunan yang baru. Daun-daun yang lebih cantik dan lebih hijau." Ibu tersenyum, tangan kanannya mengusap pipi kiriku yang kemerahan. Sedang tangan kirinya menggenggam jemariku. Ah, tangan ibu memang ajaib. Sentuhannya selalu menghangatkan bagian paling dingin sekalipun juga menyembuhkan bagian paling sakit sekalipun. Betapa berharganya ibu bagi anak laki-laki berambut coklat ini.
"Seperti itulah, George. Terkadang hidup memaksa kita untuk harus merelakan sesuatu yang berharga pergi," ucap ibu dengan nada paling lembut.
*****
_California, 15 Oktober 2018_
Hari ini, aku kembali mengingatnya, bu. Mengingat setiap detil nasihatmu, pada musim gugur 16 tahun lalu. Musim gugur terakhir dimana aku tak akan pernah lupa senyum terindah milikmu, sebelum engkau gugur dan membiarkan aku menjadi pohon tak berdaun.
********
Cirebon, 9 Des 2018
_California, 15 Oktober 2018_
Hari ini, aku kembali mengingatnya, bu. Mengingat setiap detil nasihatmu, pada musim gugur 16 tahun lalu. Musim gugur terakhir dimana aku tak akan pernah lupa senyum terindah milikmu, sebelum engkau gugur dan membiarkan aku menjadi pohon tak berdaun.
********
Cirebon, 9 Des 2018
#penaiaibbc
#kuisDialogTag
#juara2
#kuisDialogTag
#juara2
Cerpen | Terjebak Pesona Ustad
(Part ke se ki an)
Karya: Ati Satiyah
Terlihat dari tarikan di kedua ujung bibirnya, dia tersenyum, sambil menengadahkan kepala dan memejamkan matanya. Tapi, aku bingung, apa yang membuatnya seperti itu? Mungkinkah ia malu, karena tertangkap basah sedang menoleh ke arahku, atau dia tidak kuasa menatap pesona perempuan yang duduk tepat di sebelahku.
Aku sudah mencoba untuk tidak peduli, tapi aku belum bisa. Mataku semakin kurang ajar, saat melihatnya tampil rapi dengan balutan jas almamater dan dasi yang tersemat di lehernya. Hati dan pikiranku bergemuruh kembali, seolah-olah mereka sedang tawuran di dalam diriku. Aku bingung sendiri harus memilih yang mana, hati atau pikiran?
Hati menyuruh mata untuk berkedip, tapi pikiran seolah memonopoli mata untuk terus menatap. Hati mencoba berkompromi dengan pikiran untuk tidak menguasai seluruh anggota tubuhku mengaguminya, namun pikiran tak mau kalah, dia mendoktrin seluruh anggota tubuhku untuk selalu mengaguminya.
Pria itu sudah berani melubangi benteng yang telah aku tutup rapat agar tidak mudah ditembus. Tapi nyatanya, dia berhasil. Aku jatuh cinta padanya.
"Selamat, Bung! Kamu berhasil mendekati sesuatu yang aku hindari."
#prolog cerpen
Karya: Ati Satiyah
Terlihat dari tarikan di kedua ujung bibirnya, dia tersenyum, sambil menengadahkan kepala dan memejamkan matanya. Tapi, aku bingung, apa yang membuatnya seperti itu? Mungkinkah ia malu, karena tertangkap basah sedang menoleh ke arahku, atau dia tidak kuasa menatap pesona perempuan yang duduk tepat di sebelahku.
Aku sudah mencoba untuk tidak peduli, tapi aku belum bisa. Mataku semakin kurang ajar, saat melihatnya tampil rapi dengan balutan jas almamater dan dasi yang tersemat di lehernya. Hati dan pikiranku bergemuruh kembali, seolah-olah mereka sedang tawuran di dalam diriku. Aku bingung sendiri harus memilih yang mana, hati atau pikiran?
Hati menyuruh mata untuk berkedip, tapi pikiran seolah memonopoli mata untuk terus menatap. Hati mencoba berkompromi dengan pikiran untuk tidak menguasai seluruh anggota tubuhku mengaguminya, namun pikiran tak mau kalah, dia mendoktrin seluruh anggota tubuhku untuk selalu mengaguminya.
Pria itu sudah berani melubangi benteng yang telah aku tutup rapat agar tidak mudah ditembus. Tapi nyatanya, dia berhasil. Aku jatuh cinta padanya.
"Selamat, Bung! Kamu berhasil mendekati sesuatu yang aku hindari."
#prolog cerpen
Friday, January 25, 2019
Subscribe to:
Comments (Atom)
Tentang Kami
Featured Post
Mengapa Kita Harus Menulis?
Oleh : Wawat Qomariyah “Orang boleh pandai setinggi langit tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dari sejar...

Teks Singkat
Menulis adalah pengikat ilmu, dengannya dunia bisa terlihat secara gamblang. Ilmu pun tak akan pernah pupus sampai semua orang berhenti berkarya dan menulis. Maka menulislah, karena itu adalah hobi para pemikir dan cendikiawan. Pena IAI Bunga Bangsa Cirebon, bersinergi membangun budaya membaca dan menulis. Mari berkontribusi untuk selalu mendukung kegiatan positif ini.
Arsip blog
Recent Post
Popular Posts
-
Bila kita banyak membaca buku novel atau cerpen, tentu akan menemui perbincangan antartokoh. perbincangan ini sangat memberi bumbu sed...
-
Oleh Dewi Pribadi Kata mereka aku gila Karena aku menjatuhkan cinta Pada dia begitu saja Kata mereka aku gila Karena aku jatuh cinta Pada di...
-
Oleh : Wawat Qomariyah Untukmu yang kunamai 'Dia' dalam setiap do'aku. Maaf aku tak pernah tahu namamu. Jangankan tah...
-
Sumber gambar: http://islamkafah.com Oleh: Iskandar Di kampungku Kalau ada seseorang Yang selalu sendirian, kesepian, dan da...
-
Oleh: Iskandar Kapan dari mana Namamu nostalgia Pada paru-paruku Yang bernafas hampa Tanpa drama Kapan dari mana Rin...
Created with by Pena IAI BBC | Distributed By Blogspot Themes